Biografi Max Weber
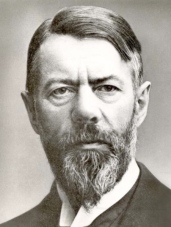 Max Weber lahir di Erfurt, Jerman, 21 April 1864, berasal dari keluarga kelas menengah. Perbedaan penting antara. Max Weber
Max Weber lahir di Erfurt, Jerman, 21 April 1864, berasal dari keluarga kelas menengah. Perbedaan penting antara. Max Weber
kedua orang tuanya berpengaruh besar
terhadap orientasi intelektual dan perkembangan psikologi Weber. Ayahnya
seorang birokrat yang kedudukan politiknya relatif penting, dan menjadi
bagian dari kekuasaan politik yang mapan dan sebagai akibatnya
menjauhkan diri dari setiap aktivitas dan dan idealisme yang memerlukan
pengorbanan pribadi atau yang dapat menimbulkan ancaman terhadap
kedudukannya dalam sistem. Lagi pula sang ayah adalah seorang yang
menyukai kesenangan duniawi dan dalam hal ini, juga dalam berbagai hal
lainnya, ia bertolak belakang dengan istrinya. Ibu Marx Weber adalah
seorang Calvinis yang taat, wanita yang berupaya menjalani kehidupan
prihatin (asetic) tanpa kesenangan seperti yang sangat menjadi
dambaan suaminya. Perhatiannya kebanyakan tertuju pada aspek kehidupan
akhirat; ia terganggu oleh ketidaksempurnaan yang dianggapnya menjadi
pertanda bahwa ia terganggu oleh ketidaksempurnaan yang dianggapnya
menjadi pertanda bahwa ia tak ditakdirkan akan mendapat keselamatan di
akhirat. Perbedaan mendalam antara kedua pasangan ini menyebabkan
ketegangan perkawinan mereka dan ketegangan ini berdampak besar terhadap
Weber.
Karena tak mungkin menyamakan diri
terhadap pembawaan orang tuanya yang bertolak belakang itu, Weber kecil
lalu berhadapan dengan suatu pilihan jelas (Marianne Weber, 1975:62).
Mula-mula ia memilih orientasi hidup ayahnya, tetapi kemudian tertarik
makin mendekati orientasi hidup ibunya. Apapun pilihannya, ketegangan
yang dihasilkan oleh kebutuhan memilih antara pola yang berlawanan itu
berpengaruh negatif terhadap kejiwaan Weber. Ketika berumur 18 tahun
Weber minggat dari rumah, belajar di Universitas Heildelberg. Weber
telah menunjukkan kematangan intelektual, tetapi ketika masuk
universitas ia masih tergolong terbelakang dan pemalu dalam bergaul.
Sifat ini cepat berubah ketika ia condong pada gaya hidup ayahnya dan
bergabung dengan kelompok mahasiswa saingan kelompok mahasiswa ayahnya
dulu. Secara sosial ia mulai berkembang, sebagian karena terbiasa minum
bir dengan teman-temannya. Lagipula ia dengan bangga memamerkan parutan
akibat perkelahian yang menjadi cap kelompok persaudaraan mahasiswa
seperti itu. Dalam hal ini Weber tak hanya menunjukkan jati dirinya sama
dengan pandangan hidup ayahnya tetapi juga pada waktu itu memilih karir
bidang hukum seperti ayahnya.
Setelah kuliah tiga semester Weber
meninggalkan Heidelberg untuk dinas militer dan tahun 1884 ia kembali ke
Berlin, ke rumah orang tuanya, dan belajar di Universitas Berlin. Ia
tetap disana hampir 8 tahun untuk menyelesaikan studi hingga mendapat
gelar Ph.D., dan menjadi pengacara dan mulai mengajar di Universitas
Berlin. Dalam proses itu minatnya bergeser ke ekonomi, sejarah dan
sosiologi yang menjadi sasaran perhatiannya selama sisa hidupnya. Selama
8 tahun di Berlin, kehidupannya masih tergantung pada ayahnya, suatu
keadaan yang segera tak disukainya. Pada waktu bersamaan ia beralih
lebih mendekati nilai-nilai ibunya dan antipatinya terhadapnya
meningkat. Ia lalu menempuh kehidupan prihatin (ascetic) dan
memusatkan perhatian sepenuhnya untuk studi. Misalnya, selama satu
semester sebagai mahasiswa, kebiasaan kerjanya dilukiskan sebagai
berikut : “Dia terus mempraktikkan disiplin kerja yang kaku, mengatur
hidupnya berdasarkan pembagian jam-jam kegiatan rutin sehari-hari ke
dalam bagian-bagian secara tepat untuk berbagai hal. Berhemat menurut
caranya, makan malam sendiri dikamarnya dengan 1 pon daging sapi dan 4
buah telur goreng” (Mitzman, 1969/1971:48; Marianne Weber, 1975:105).
Jadi, dengan mengikuti ibunya, Weber menjalani hidup prihatin, rajin,
bersemangat kerja, tinggi dalam istilah modern disebut Workaholic
(gila kerja). Semangat kerja yang tinggi ini mengantarkan Weber menjadi
profesor ekonomi di Universitas Heidelberg pada 1896. Pada 1897, ketika
karir akademis Weber berkembang, ayahnya meninggal setelah terjadi
pertengkaran sengit antara mereka. Tak lama kemudian Weber mulai
menunjukkan gejala yang berpuncak pada gangguan safaf. Sering tak bisa
tidur atau bekerja, dan enam atau tujuh tahun berikutnya dilaluinya
dalam keadaan mendekati kehancuran total. Setelah masa kosong yang lama,
sebagian kekuatannya mulai pulih di tahun 1903, tapi baru pada 1904,
ketika ia memberikan kuliah pertamanya (di Amerika) yang kemudian
berlangsung selama 6,5 tahun, Weber mulai mampu kembali aktif dalam
kehidupan akademis tahun 1904 dan 1905 ia menerbitkan salah satu karya
terbaiknya. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism.
Dalam karya ini Weber mengumumkan besarnya pengaruh agama ibunya di
tingkat akademis. Weber banyak menghabiskan waktu untuk belajar agama
meski secara pribadi ia tak religius.
Meski terus diganggu oleh masalah
psikologis, setelah 1904 Weber mampu memproduksi beberapa karya yang
sangat penting. Ia menerbitkan hasil studinya tentang agama dunia dalam
perspektif sejarah dunia (misalnya Cina, India, dan agama Yahudi kuno).
Menjelang kematiannya (14 Juni 1920) ia menulis karya yang sangat
penting, Economy and Society. Meski buku ini diterbitkan, dan
telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa, namun sesungguhnya karya
ini belum selesai. Selain menulis berjilid-jilid buku dalam periode ini,
Weber pun melakukan sejumlah kegiatan lain. Ia membantu mendirikan German Sociological Society
di tahun 1910. Rumahnya dijadikan pusat pertemuan pakar berbagai cabang
ilmu termasuk sosiologi seperti Georg Simmel, Alfred, maupun filsuf dan
kritikus sastra Georg Lukacs (Scaff, 1989:186:222). Weberpun aktif
dalam aktivitas politik dimasa itu. Ada ketegangan dalam kehidupan Weber
dan, yang lebih penting, dalam karyanya, antara pemikiran birokratis
seperti yang dicerminkan oleh ayahnya dan rasa keagamaan ibunya.
Ketegangan yang tak terselesaikan ini meresapi karya Weber maupun
kehidupan pribadinya.


